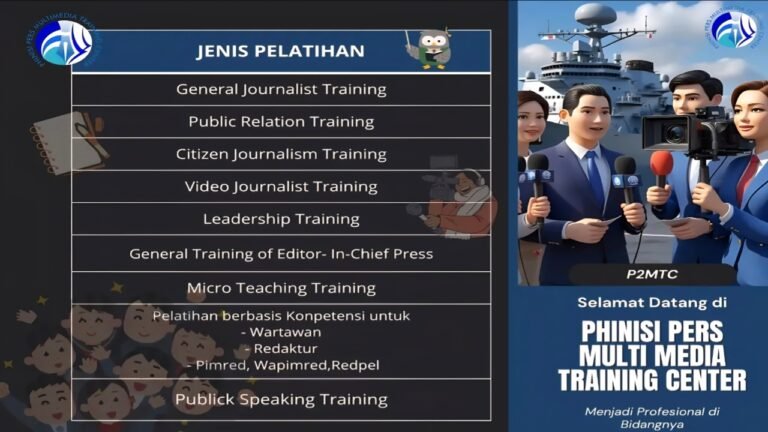Oleh: Damai Hari Lubis, Penulis adalah Pengamat KUHP (Kebijakan Umum Hukum dan Politik)
Pada pertengahan Desember 2025, saya berada di Solo untuk bersilaturahmi dengan seorang tokoh masyarakat yang selama ini aktif mendukung gerakan sosial dan advokasi hukum. Kunjungan itu mengingatkan saya pada rangkaian advokasi pada 2023 di Pengadilan Negeri Surakarta, ketika kami mendampingi dua aktivis, Bambang Tri Mulyono dan Gus Nur, dalam perkara yang berkaitan dengan dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo.
Bagi kami, perkara tersebut sejak awal bukan sekadar soal individu, melainkan tentang ruang kritik warga negara terhadap kekuasaan. Kritik dan gugatan adalah bagian dari mekanisme kontrol publik dalam negara demokratis.
Di sela-sela keberadaan saya di Solo, Ketua Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA), Eggi Sudjana, menghubungi saya. Ia mengirimkan salinan surat pencekalan dari Direktorat Jenderal Imigrasi yang melarangnya bepergian ke luar negeri karena statusnya sebagai tersangka. Status hukum itu tidak terlepas dari aktivitas TPUA yang pada 2023 mengajukan gugatan perdata dan pada 2024 melaporkan dugaan tersebut melalui pengaduan masyarakat ke Mabes Polri. Saya terlibat langsung sebagai konseptor dalam kedua langkah hukum tersebut.
Yang mengusik bukan hanya pencekalan itu sendiri, melainkan informasi lanjutan yang disampaikan Eggi. Ia mengaku dihubungi oleh pihak yang mengklaim sebagai aparat dan menyarankan agar perkara tersebut dapat “diselesaikan” apabila ia bersedia menyampaikan permohonan maaf kepada Jokowi.
Pengalaman itu bukan hal baru bagi saya. Menjelang pemanggilan ketiga untuk pemeriksaan di Polda Metro Jaya, saya pun menerima pesan serupa dari seorang advokat: agar membuat surat pernyataan permintaan maaf. Situasi ini memunculkan pertanyaan mendasar—kesalahan apa yang sebenarnya kami lakukan sehingga permintaan maaf dianggap sebagai jalan keluar hukum?
Jika yang dipersoalkan adalah kritik dan upaya hukum terhadap seorang pejabat publik, maka persoalan ini menyentuh prinsip dasar negara hukum. Dalam demokrasi konstitusional, gugatan dan laporan hukum bukanlah serangan personal. Ia merupakan hak warga negara yang dijamin oleh hukum, sepanjang dilakukan sesuai prosedur dan didasarkan pada data serta argumentasi yang dapat diuji.
Saran agar tersangka meminta maaf demi meredam proses hukum justru menimbulkan kesan bahwa hukum dapat dinegosiasikan di luar mekanisme peradilan. Jika praktik semacam ini dianggap lumrah, maka ruang kritik publik berpotensi menyempit, dan hukum kehilangan fungsinya sebagai sarana pencarian kebenaran.
Pengalaman ini menunjukkan bahwa demokrasi tidak hanya diuji melalui pemilu, tetapi juga melalui cara negara merespons kritik warganya. Permintaan maaf tidak semestinya menjadi pengganti proses hukum. Dalam negara hukum, perbedaan pendapat harus diselesaikan melalui pembuktian yang terbuka dan adil, bukan melalui tekanan simbolik yang berpotensi membungkam. (*)