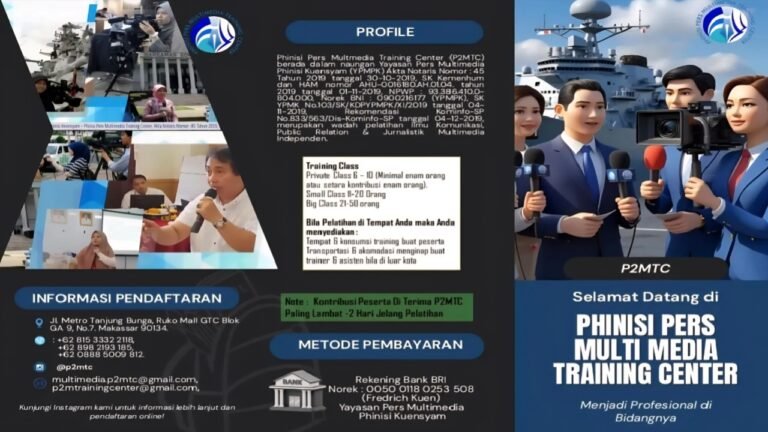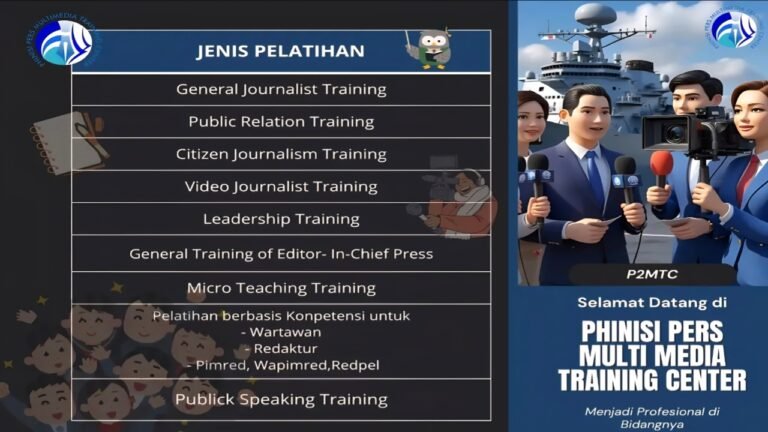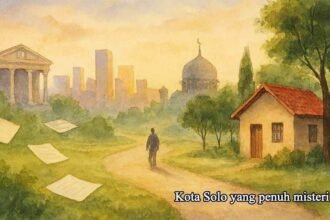Data terbaru menunjukkan pengguna internet di Indonesia sudah mencapai lebih dari 229 juta orang.
Platform yang paling banyak digunakan adalah WhatsApp, Facebook, TikTok, Instagram, YouTube, dan X.
Adapun perilaku penggunaan internet terbagi: 24,8 persen untuk mengakses media sosial, 15 persen untuk membaca berita online, 15 persen untuk transaksi keuangan, dan sisanya untuk berbagai aktivitas lain.
Menariknya, hasil Digital News Report 2025 mencatat bahwa 57 persen responden di Indonesia memperoleh berita dan informasi melalui media sosial. Bukan dari media mainstream.
Artinya, lini masa media sosial kini telah berubah menjadi instrumen opini publik, bukan sekadar tempat berbagi kabar atau obrolan ringan.
Pertanyaannya, apa yang terjadi bila yang beredar dan viral di media sosial justru hoaks?
Konten berupa miscaption, deepfake, ajakan palsu, atau narasi jahat berbasis sesat pikir (logical fallacy)?
Kerusuhan pada akhir Agustus lalu menjadi contoh nyata betapa berbahayanya fenomena ini.
Ledakan Hoaks
Kementerian Kominfo mencatat 1.923 hoaks terdeteksi sepanjang 2024, dengan dominasi isu politik dan keamanan.
- Iklan Google -
Fakta ini mengindikasikan adanya produksi konten hoaks yang sistematis, entah oleh individu maupun kelompok, dengan tujuan menciptakan keresahan publik.
Apalagi, budaya “forward” di grup WhatsApp kian mengakar.
Satu pesan tanpa verifikasi bisa berlipat ganda penyebarannya hanya dalam hitungan menit.
Empat Ancaman Serius
Ada setidaknya empat bentuk konten yang menjadi ancaman serius bagi masyarakat digital di Indonesia:
1. Miscaption
Yaitu foto atau video lama yang diberi keterangan waktu dan tempat baru. Contohnya, video mahasiswa menyerbu ruang sidang DPR RI tahun 1998, tetapi diberi label seolah terjadi pada Agustus kemarin. Atau rekaman lama Presiden Prabowo mengunjungi rumah mantan Presiden Jokowi, dipoles seolah terjadi di tengah kerusuhan terbaru.
2. Deepfake
Teknologi sintetis berbasis AI yang meniru audio atau visual tokoh. Misalnya, rekaman suara Menteri Keuangan Sri Mulyani yang dipalsukan dengan kalimat kontroversial. Investigasi MAFINDO menggunakan detektor watermark SynthID membuktikan rekaman itu hasil rekayasa.
3. Ajakan Palsu
Siaran broadcast yang mengatasnamakan organisasi atau kelompok mahasiswa untuk mengajak aksi, lengkap dengan tanggal, jam, dan lokasi. Faktanya, tidak ada agenda resmi. Tujuannya jelas: mengarahkan massa ke titik rawan untuk memicu bentrokan spontan.
4. Narasi Sesat Pikir (Logical Fallacy)
Bentuk manipulasi opini melalui argumen menyesatkan. Bisa berupa meme, flyer, atau postingan teks yang terlihat meyakinkan, padahal cacat logika.
Beberapa jenis yang sering muncul:
- Ad Hominem: menyerang pribadi, bukan argumen.
- Straw Man: melebih-lebihkan atau memutarbalikkan argumen lawan.
- Bandwagon: menganggap benar karena banyak orang percaya.
- False Dichotomy: memaksa pilihan seolah hanya ada dua.
- Appeal to Authority: menganggap sahih hanya karena disampaikan figur otoritas.
Memahami sesat pikir ini penting agar masyarakat lebih kritis dan tidak mudah terperangkap dalam jebakan logika palsu.
Dampak Berlapis
Keempat jenis konten tersebut—miscaption, deepfake, ajakan palsu, dan sesat pikir—bila muncul bersamaan akan saling menguatkan.
- Miscaption membangkitkan emosi.
- Deepfake meruntuhkan kepercayaan terhadap otoritas.
- Ajakan palsu memicu kerumunan rawan bentrok.
- Sesat pikir meracuni pola pikir publik.
Kombinasi ini bisa menciptakan badai disinformasi yang berbahaya.
Peran Pemerintah
Mayoritas masyarakat Indonesia tidak memiliki kapasitas verifikasi informasi yang memadai. Di sinilah negara harus hadir.
Saya mengusulkan pembentukan command room satu atap yang khusus bertugas mendeteksi disinformasi secara real time.
Tugasnya:
- Analisis cepat konten hoaks, deepfake, miscaption, dan ajakan palsu.
- Menyampaikan klarifikasi dalam hitungan menit, bukan menunggu esok hari.
- Menggunakan semua kanal: televisi, radio, media online, YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, X, hingga broadcast WhatsApp.
Dalam situasi genting, perlu juga jumpa pers harian untuk mengabarkan kondisi terkini dan meluruskan hoaks yang beredar.
Kecepatan menjadi kunci. Studi APJII 2024 mencatat, rata-rata warganet Indonesia menghabiskan 3 jam 6 menit per hari di media sosial, dengan 167 juta pengguna aktif.
Maka, jika klarifikasi lambat, hoaks akan lebih dulu menguasai opini publik.
Pelajaran dari Kerusuhan Agustus
Kerusuhan 2025 memberi pelajaran berharga: debunking harus dilakukan secepat mungkin.
Pemerintah, lembaga, dan media perlu bersinergi menghadirkan bukti terverifikasi agar hoaks kehilangan daya sebar.
Jika tidak, masyarakat akan terus terjebak dalam siklus salah informasi yang tak hanya membingungkan, tetapi juga berpotensi mengguncang stabilitas sosial dan politik.
Penulis adalah Ketua Dewan Pembina Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Pusat, Guru Besar Universitas Negeri Makassar, dan Wakil Rektor Universitas Jayabaya Jakarta.