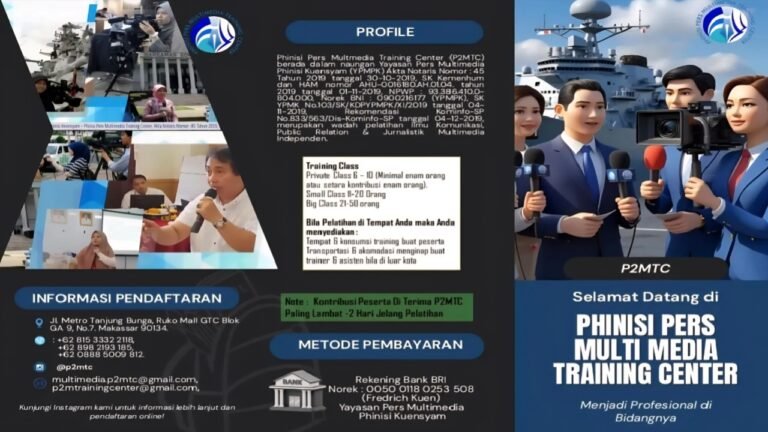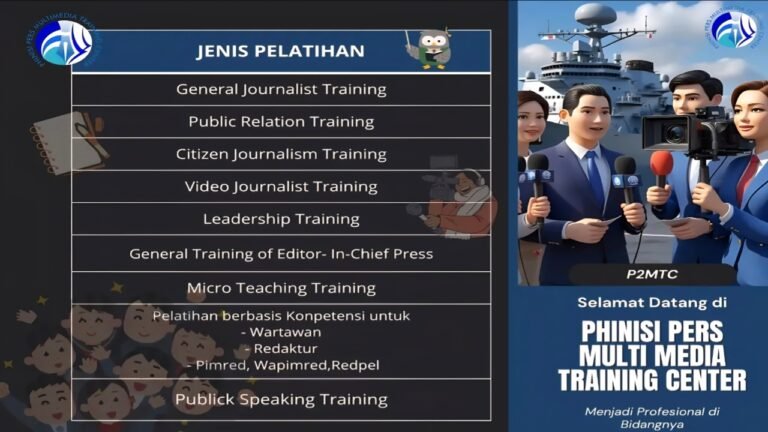MEDIAPESAN – Di tengah demokrasi yang diklaim semakin matang, ancaman terhadap kebebasan pers justru kian halus bentuknya.
Kini, bukan lagi sensor atau kekerasan fisik yang paling menakutkan bagi jurnalis, melainkan gugatan hukum yang disusun rapi—seringkali dengan nominal fantastis dan alasan yang tipis.
Fenomena ini dikenal sebagai Unjustified Lawsuit Against Press (ULAP) — gugatan hukum yang tidak beralasan atau berlebihan terhadap media dan jurnalis, dengan tujuan membungkam kritik atau pemberitaan investigatif.
Menurut Aliansi Jurnalis Independen (AJI), ULAP adalah bentuk serangan yang paling sering digunakan untuk menekan media.
Tahun 2023 mencatat 89 kasus serangan terhadap pers, tertinggi dalam satu dekade terakhir.
Gugatan terhadap Tempo oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman senilai Rp200 miliar hanyalah puncak dari gunung es.
Pola Serangan: Dari Pejabat hingga Korporasi
ULAP sering muncul dari pihak-pihak dengan kekuasaan besar: pejabat, korporasi, bahkan lembaga negara.
Tujuannya bukan untuk mencari keadilan, tapi untuk menguras energi, waktu, dan dana media melalui proses hukum panjang.
1. Syahrul Yasin Limpo vs Tempo (2019)
- Iklan Google -
Tempo digugat Rp100 miliar karena laporan investigatif “Gula Impor Gelap.”
Tempo dinilai telah mengikuti kode etik, namun tetap harus menjalani proses panjang yang melelahkan.
AJI menyebutnya sebagai contoh klasik ULAP yang menargetkan independensi redaksi.
2. Pertamina vs Kompas.com (2022)
Gugatan Rp500 miliar dilayangkan karena pemberitaan soal dugaan korupsi di Blok Cepu.
Hakim menegaskan berita itu sah sebagai bentuk kontrol sosial, tapi Pertamina tetap menggugat biaya hukum.
Akibatnya, muncul self-censorship di kalangan jurnalis energi.
3. Ridwan Kamil vs Tribunnews.com (2021)
Gugatan Rp150 miliar terkait pemberitaan dugaan penyalahgunaan anggaran infrastruktur akhirnya ditolak pengadilan.
Namun, prosesnya memakan waktu 18 bulan.
AJI menilai, kasus ini mencerminkan “pembalasan dengan kekuasaan.”
4. KPK vs Narasi TV (2023)
KPK menuntut Rp300 miliar atas dokumenter “KPK vs Negara.”
Human Rights Watch (HRW) menilai ini sebagai upaya pembungkaman internal, di mana lembaga antikorupsi justru menggunakan jalur hukum untuk menekan kritik terhadap dirinya sendiri.
5. Freeport Indonesia vs Mongabay.co.id (2024)
Gugatan Rp400 miliar terhadap Mongabay atas liputan dampak lingkungan di Papua memperlihatkan pola baru: ULAP terhadap media lingkungan.
Kasus ini dikategorikan sebagai SLAPP (Strategic Lawsuit Against Public Participation), karena tujuannya untuk menghentikan partisipasi publik dalam isu ekologis.
Dampak: Meningkatkan risiko bagi jurnalis lingkungan, di mana Mongabay harus alokasikan dana hukum daripada liputan lapangan.
Ketika Hukum Jadi Senjata, Bukan Pelindung
UU Pers No. 40 Tahun 1999 jelas menyebut: sengketa pemberitaan harus diselesaikan melalui Dewan Pers terlebih dahulu.
Namun, banyak penggugat memilih jalur perdata atau pidana langsung ke pengadilan umum—melompati mekanisme itu.
Menurut Human Rights Watch (HRW), pola ULAP meningkat 30% sejak 2023, terutama pasca-Pilpres 2024.
Tren ini menandai pergeseran dari kekerasan fisik ke “kekerasan hukum.”
Di lapangan, dampaknya nyata: media kehilangan dana liputan karena biaya hukum, wartawan memilih berhati-hati pada isu-isu sensitif, dan publik kehilangan hak untuk tahu.
Rekomendasi: Menjaga Pers, Menjaga Demokrasi
AJI, Komnas HAM, dan LBH Pers menyarankan langkah-langkah konkret:
1. Aparat penegak hukum harus menolak dan menginvestigasi pelaku ULAP.
2. Revisi KUHP agar jurnalis terlindungi dari gugatan abusif dan kriminalisasi.
3. Dana darurat pers untuk membantu media kecil menghadapi tekanan hukum.
Karena jika ULAP dibiarkan, bukan hanya media yang kehilangan suaranya—tetapi masyarakat yang kehilangan hak untuk mendapat informasi benar.
Seperti kata seorang jurnalis senior; “Mereka tak perlu membredel kita. Cukup dengan menggugat Rp500 miliar, redaksi bisa lumpuh.”
Dan di situlah, demokrasi perlahan kehilangan nafasnya.